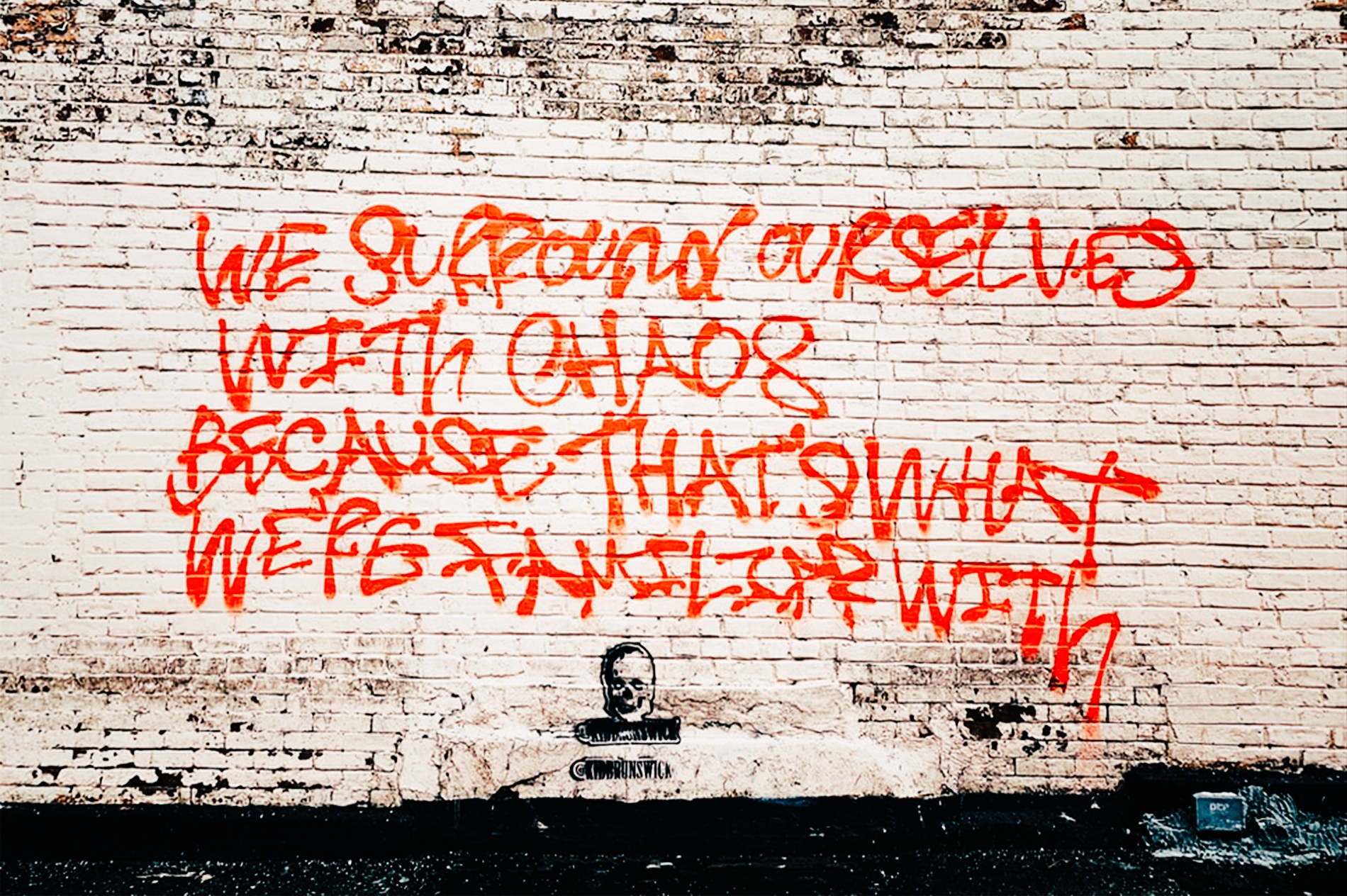“Kita tuan pada masing-masing”.
Dalam “Obituari Air Mata” milik Sisir Tanah, kalimat pertama yang didengungkan yaitu “Kita tuan pada masing-masing”, tak perlu bersusah memaknai dengan filosofis atau memakai dengan termin-termin sastra yang dalam, Sisir tanah secara naratif menegaskan bahwa setiap manusia adalah pemimpin diri mereka sendiri, manusia adalah tuan untuk apa yang mereka hirup, apa yang mereka pijak, titik.
***
Papua, dengan segala keindahan alam, struktur geogafis yang beragam, dan semua utopia tentang pulau paling timur di peta Indonesia. Sudah terlalu usang kita mendengar tentang kerukunan warga, destinasi wisata, atau apapun yang membuat Papua disulap menjadi komoditas nomber wahid oleh pemerintah. Banyaknya pemukiman warga kekurangan air bersih, akibat dari pembangunan infrastruktur pemerintah juga penggusuran hutan yang ditanam sawit. Fungsi adat dihilangkan perlahan, memberikan keleluasaan membantai warga adat agar dipaksa mengikuti keinginan pemerintah dengan slogan lapuknya “NKRI Harga Mati!”.
1 Desember 1963 diperingati sebagai hari kemerdekaan Papua Barat oleh Kolonial Belanda, dan dalam waktu singkat, Indonesia (yang didukung negara barat) melakukan referendum bersama PBB untuk kembali mengambil alih tanah Papua, tanpa melibatkan warga Papua. Hanya 1.000 orang –yang pasti dibawah intimidasi serta penyiksaan- dari 800.000 penduduk yang dilibatkan, tanpa perundingan. Disinilah awal mula gerakan militer Indonesia mulai menguasai Papua, dibawah komando Sang Jendral Jagal (Soeharto), semua elemen masyarakat yang dicurigai mengingkari azas NKRI diberantas. Tercatat 50 tahun sudah lebih dari ratusan ribu orang yang hilang dan meninggal, tanpa kejelasan hukum.
Intrik politik Papua terdata sebagai politik yang sangat rumit, kejelasan akan administrasi, juga berbagai konflik internal masyarakat, dan agresi militer yang menguasai hampir seluruh titik di tanah cendrawasih. Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang bersikukuh ingin melepaskan diri dari NKRI terus mendapat ancaman nyata dari pemerintah dan militer. Tak ada yang bisa ditolerir dari pembunuhan, kedua pihak melakukannya, tetapi yang harus dicatat, warga sipil, tanah, tempat tinggal, identitas yang di permainkan pemerintah, itulah kebusukan terbesar dalam program ‘pemutihan’ Papua!
Musik Sebagai Media Subversif
Pada periode tahun 1970, di Papua terbentuk sebuah grup musik bernama Mambesak. Sebelum terkenal dengan nama Mambesak,cikal bakal awalnya adalah sebuah grup band dengan nama Manyori (burung nuri) yang berdiri di Kampus Uncen (Universitas Cenderawasih) Jayapura dan mulai berkiprah di awal tahun 1970-an. Awalnya grup ini beranggotakan Arnold Ap yang ketika itu menjadi Kepala Museum Uncen, Sam Kapissa dan Jopie Jouwe. Pada tahun 1972, Band Manyori mengiringi lagu-lagu rohani di Gereja Harapan, Abepura yang kemudiang menggugah mereka untuk mulai mengembangkan lagu-lagu rohani dalam bahasa daerah mereka, dalam hal ini adalah bahasa Biak Numfor. Jelas saja hal ini awalnya mendapat tentangan dari tetua-tetua adat karena saat misionaris membawa pengaruh agama Kristen ke Papua, mereka mengkafirkan lagu, seni ukir, dan seluruh aspek kebudayaan di Papua, khususnya di kawasan Teluk Cenderawasih.
Grup Mambesak tercatat berdiri pada 15 Agustus 1978 dengan mulai mengisi acara hiburan lepas senja di halaman Museum Loka Budaya (Museum Antropologi) Universitas Cenderawasih di Jayapura. Nama Mambesak dipilih baru ditetapkan mengganti Manyori pada penetapan pembentukan pengurus Mambesak. Nama ini dipilih karena dalam bahasa Biak-Numfor, mambesak berarti burung kuning atau burung cenderawasih, dihormati oleh semua suku-suku di seluruh Papua Barat sebagai mahkota kepala suku. Sedangkan Manyori yang berarti burung nuri dalam bahasa Biak-Numfor hanya merupakan burung suci bagi orang Biak–Numfor saja. Pada tanggal 17 Agustus 1978, Mambesak menampilkan lagu-lagu dan tari-tarian rakyat Papua hasil galian mereka di aula Uncen. Sejak saat itulah Mambesak kemudian secara rutin menyanyikan lagu dan tari-tarian budaya Papua di halaman museum Uncen, yang dijuluki sebagai “Istana Mambesak”.
Mambesak mewakili apa yang sebetulnya terjadi di Papua, menyuarakan suara masyarakat Papua. Tak pelak mereka didapuk sebagai salah satu tokoh kelompok yang mewakili masyarakat. Pergerakan yang dilakukan Mambesak juga beririsan dengan situasi politik yang ada di Papua, yang sering disebut Papua Barat.
Selain Mambesak, juga semakin banyak musisi-musisi dari Papua yang lahir, melalui musik mereka menyuarakan rasa ketidak adilan yang terjadi disana. Salah satu contoh yaitu Yab Sartope, berkolaborasi bersama Yolanda Tatogo dan Mateus Auwe, mereka mengeluarkan sebuah lagu dengan judul “Jangan Diam, Papua”, sebuah lagu yang meceritakan tentang kekejian aparat dengan tindakan represifnya menghajar masyarakat setempat, bumi dihanguskan, hutan tempat mereka tinggal dibakar. Sepenggal lirik “Oh Papua, darahku tak harus merah, tulangku tak mesti putih. Jangan tanya arti kemerdekaan diri, lawanlah!”, tak habis kata yang harus diucap mendengar jerit tangis warga yang selalu diintimidasi.
Hari ini kerakusan perkosa bumi kami
Rendah sudah kini harga diri
Diam sama saja mati
***
Selain musisi asli Papua, musisi dari luar Papua pun ikut serta bersolidaritas menciptakan lagu untuk –setidaknya- memberikan bantuan energi melalui musik. Sisir Tanah, Morgue Vanguard, dan Last Scientist adalah beberapa musisi yang turut menyumbangkan energi bagi masyarakat Papua.
Yang wajib dari hujan adalah basah
Yang wajib dari basah adalah tanah
Yang wajib dari tanah adalah hutan
Yang wajib dari hutan adalah tanam
Yang wajib dari tanam adalah tekad
Yang wajib dari tekad adalah hati
Yang wajib dari hati adalah kata
Yang wajib dari kata adalah tanya
Yang wajib dari tanya adalah kita
Yang wajib dari kita adalah cinta
Yang wajib dari cinta adalah mesra
Yang wajib dari mesra adalah rasa
Yang tak wajib dari rasa.. adalah luka
Lirik lagu Sisir Tanah tentang bagaimana fitrah ‘rumah’ bagi manusia, tentang cinta dan kasih alam yang diberikan kepada manusia, juga bagaimana kejinya jika terjadi ‘luka’ pada ‘rasa’ tanah manusia. Simbol tanah Papua hari ini.
Harapan Adalah Kekuatan
Lila Watson dalam sajaknya menuliskan “Jika kau datang untuk menolongku, kau buang-buang waktu saja. Tetapi jika kau datang karena kebebasanmu terikat dengan kebebasanku, maka mari kita bekerja bersama”. Harapan untuk menghentikan kekerasan di Papua Barat masih ada, dan akan selalu hidup. Musik sebagai salah satu identitas da budaya masyarakat papua sudah membuktikan bahwa musik menjadi stimulant juga katalis untuk mempersatukan masyarakat, sekecil-kecilnya menghangatkan suasana dalam riuh peluru militer yang terus berterbangan.
Bukan infrastruktur, juga kedamaian fana yang diidamkan masyarakat Papua. Tetapi tanah moyang yang seharusnya berfungsi selayaknya, dilimpahkan kepada yang berhak, taka da darah, tak ada luka. “Bukan makanan kaleng, jalan tol, atau lahan pekerjaan. Tapi kedamaian tanah yang kami inginkan. Alam sudah memberikan segalanya untuk kami, tak perlu kalian (pemerintah Indonesia) menjilat kasar tanah kami. Badan kami sudah seperti binatang dimata kalian.”, begitu ujar tokoh masyarakat Papua, Filep Karma.
Vox Papua, Vox Dei!