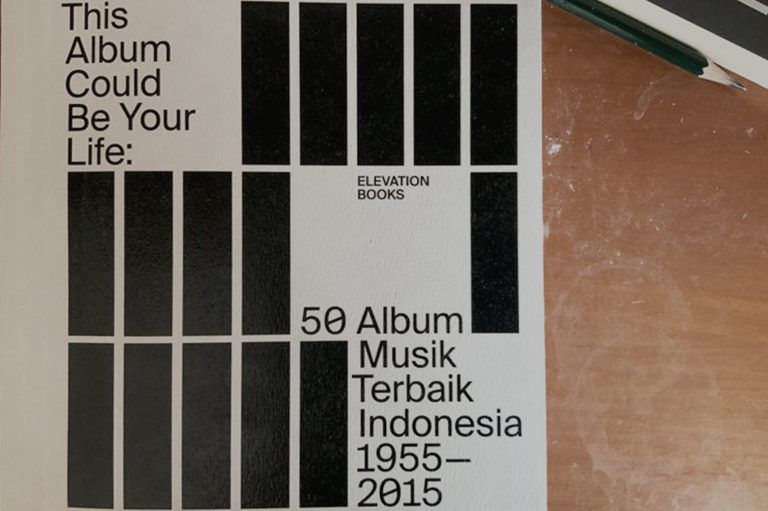Ada kalanya kita muak atau lebih tepatnya lelah dengan segala macam bentuk pelabelan. Dalam konteks musik, tak jarang kita disibukkan dengan penyebutan genre. Kita kerap kali terjebak dengan pengklasifikasian genre tertentu dari sebuah musik. Alih-alih membuat musik, band atau musisi terkadang malah dipusingkan untuk melabeli musiknya itu sendiri.
Band kami adalah metal, band kami grindcore, indie-rock, punk, jazz dan lain-lain, lengkap dengan standar-standar baku sebagai patokan. Seolah musik punk hanya bisa dikatakan sebagai punk jika ia menyertakan ketukan drum dan kocokan gitar bertempo cepat. Atau seolah musik metal atau rock, hanya berhenti pada raungan gitar penuh distorsi dan vokal berteriak. Tak boleh ada bentuk lain di luar standar-standar yang disepakati umum. Pada taraf tertentu, pengkotak-kotakan genre semacam ini malah membelenggu bahkan membatasi kreativitas.
Kita selalu sibuk mencari esensi hingga lupa bahwa yang lebih dulu hadir seharusnya bukan esensi, melainkan eksistensi. Esensi mendahuli eksistensi. Begitu kira-kira yang dapat saya simpulkan.
Bicara soal esensi dan eksistensi. Ada satu sosok yang perlu kita sertakan berdasarkan dua kata tadi (esensi & eksistensi), yakni: Jean-Paul Sartre.
Berkebalikan dari dua hal tadi: esensi, dan eksistensi, ia justru menganggap bahwa segala sesuatu—terutama manusia— eksistensinya ada lebih dulu ketimbang esensi yang melekat di dirinya. Sehingga dalam hal ini, tak pernah ada bentuk pasti dari esensi manusia. Manusia harusnya menolak segala bentuk determinasi atau fiksasi atas dirinya. Ia bebas menentukan atau memaknai dirinya sesuai dengan apa yang ia ingin maknai. Hakikat, en soi, absolutisme tak pernah ada dalam kamus Sartre. Manusia bebas menentukan dirinya sendiri sebagai apa.
Tentu kita perlu tengok sejenak mengapa ia beranggapan demikan. Faktor masa kecil salah satunya.
Meski hidup tanpa ayah saat usianya belum genap setahun, Jean-Paul Sartre, filsuf terkenal itu punya masa kecil yang bahagia. Ia sempat merasakan menjadi pusat perhatian dan kasih sayang keluarga.
Hidup bersama ibunya, Anne Marie, seorang janda muda berusia 24 tahun yang kemudian memilih untuk pulang ke rumah orang tuanya di Paris pasca ditinggal mati suaminya.
Di periode inilah Sartre merasa menjadi pusat perhatian dan pujaan keluarga. Dengan potongan rambut pirangnya yang bergelung-gelung, Sartre kecil dengan cepat menyadari sisi tampan dirinya.
Hingga satu petaka muncul selepas ia pulang dari tukang cukur bersama kakeknya dan mendapati dirinya mirip kodok dengan potongan rambut aneh. Tepat di hari itulah awal mula kejatuhannya, ia menemukan dirinya “jelek”, bermata juling dengan perawakan yang mirip kodok.
Peristiwa pulang dari tukang cukur itulah yang kemudian jadi motif hidupnya di kemudian hari, sekaligus jadi dasar penting bagi konsep eksistensialisme nya. Ia menganggap: manusia ditentukan oleh cara pandang orang lain. Lewat tatapan mata orang lain, manusia diobjektivikasi, dimampatkan dalam sebuah konsep, ide, atau sesuatu yang di luar jangkauan manusia itu sendiri.
Di hadapan objektivikasi macam itu, ada dua sikap yang ditawarkan Sartre: menyesuaikan diri secara pasif serta menerima objektivikasi itu; atau yang kedua: memberontak, menidak atas objektivikasi itu.
Sikap kedua lah yang kemudian Sartre ambil. Menurutnya, menidak atau menolak atas objektivikasi orang lain adalah sebentuk upaya mengembalikan lagi defisit kebebasannya. Baginya, tatapan orang lain hanya mereduksi diri manusia dengan sekadar label atau embel-embel A B C serta menghambat kebebasannya untuk menentukan kemungkinan-kemungkinan lain di dirinya.
Dalam kondisi menidak atas objektivikasi itu, manusia sadar, bahwa label atau konsepsi atas dirinya sifatnya sementara dan hanya satu dari sekian banyak kemungkinan-kemungkinan yang bisa diciptakan. Itulah mengapa Sartre kemudian dengan sadar menolak segala bentuk absolutisme, fiksasi, causa sui, tuhan dan hal-hal lain yang sifatnya utuh. Menurutnya, eksistensi manusia ada begitu saja tanpa motif dan tujuan. Singkatnya: absurd.
Dari sikap “penolakan” inilah kemudian muncul istilah “kontingensi”, satu kata penting dalam memahami horizon pemikiran Sartre.
Kontingensi inilah yang kemudian jadi konsekuensi yang diterima manusia atas sikapnya yang menolak segala bentuk objektivikasi, fiksasi orang lain atas dirinya. Kontingensi yang bisa dimaknai sebagai keluwesan, keterombang-ambingan, atau inkonsistensi, menuntut manusia untuk terus bergerak mencari kemungkinan atau bentuk-bentuk lain di dirinya.
Kita kadang menamainya dengan sebutan: progresivitas. Kontingensi dalam bentuknya yang lain.
Lahir dari rahim musik eksperimental bersama band terdahulunya: Zoo, Rully Sabhara, vokalis sekaligus konseptor band kemudian mengajak Wukir Suryadi, musisi etnik tradisional untuk berkolaborasi membentuk sebuah projek yang mereka namai Senyawa.
Musik Senyawa selalu diidentikan dengan isitilah “musik tradisional” karena praktiknya yang menyertakan bambu yang Wukir sulap menjadi alat musik dan ia namai sebagai Bambu Wukir.
Tentu tak sesederhana itu, hanya karena penggunaan bambu, penamaan musik tradisional tak serta merta tepat dan mewakili, meski banyak yang menamai demikian.
Jika perlu menyertakan pengklasifikasian musik atau penamaan genre, tentu hal yang paling aman adalah dengan menyebutnya sebagai musik eksperimental. Tak salah memang, tapi lagi-lagi: tak sesederhana itu.
Mereka sanggup menerjemahkan musik eksperimen dalam bentuknya yang paling liar. Menghasilkan bebunyian yang tak pernah terpetakan oleh musisi manapun. Sehingga keluar dari sekat-sekat genre yang mengekang. Mereka memperlakukan musik sebagai lahan kosong yang bebas dimaknai sebagai apapun. Hingga menciptakan kemungkinan-kemungkinan lain yang tak pernah terpikirkan praktisi musik manapun.
Mereka memaknai kata “eksperimen” yang melekat menjadi sesuatu yang benar-benar eksperimen. Mendorongnya jauh melewati batas. Melampaui istilah eksperimen itu sendiri pada titiknya yang paling jauh. Keluar dari stigma musik eksperimen kebanyakan, yang pada praktiknya malah seragam.
Di hadapan mereka, pengotakan genre seolah tak penting. Jika ada yang menamai musik mereka musik tradisional, sah-sah saja. Death Metal? Tentu boleh. Grindcore? Apa salahnya. Punk? Siapa peduli. Pelabelan macam itu sudah bukan lagi persoalan. Tepat saat label itu disematkan, di saat itupula lah mereka “menidak” dan menolak objektivikasi siapapun yang mencoba menerjemahkan “esensi”—dalam hal ini musik—mereka. Dalam kasus ini, upaya mereka menerjemahkan ide “eksintensi mendahului esensi” yang Sarte tawarkan berhasil, tanpa perlu terbebani dengan pandangan-pandangan yang orang lain, “the other”,Liyan sematkan. Pencarian “esensi” yang belum akan selesai.